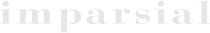Diskusi
Ranperpres Terorisme: Ancaman Negara Hukum, HAM, dan Demokrasi?
Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar diskusi bertajuk “Ranperpres Terorisme: Ancaman Negara Hukum, HAM, dan Demokrasi?” pada Senin (12/01/2026), bertempat di Sadjoe Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Imparsial, diskusi berlangsung pada Pukul 10.30 hingga 13.30 WIB.
Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani Mengatakan draft Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, jelas bahwa wacana ini merupakan upaya memperluas peran militer ke dalam ranah sipil. Ini mengingatkan kita pada draft RUU Keamanan Nasional yang pernah muncul dan akhirnya ditolak oleh masyarakat sipil karena potensi seriusnya terhadap kebebasan sipil dan akuntabilitas negara.
Yang paling mengkhawatirkan adalah langkah ini tampak sebagai kesinambungan dari upaya memperkuat peran militer di berbagai aspek kehidupan publik, termasuk dalam penanganan terorisme, tanpa menjawab persoalan fundamental: bagaimana mekanisme koreksi dan akuntabilitas ketika militer melakukan pelanggaran? Hingga kini militer masih tunduk dalam peradiilan militer belum tunduk pada peradilan umum
Ancaman terbesar dari Rancangan Perpres Terorisme ini bukan sekedar teknis hukum, tetapi stigma yang bisa dilekatkan pada komunitas sipil, yaitu bahwa siapa pun yang dianggap mengganggu “kepentingan nasional” bisa dibidik sebagai teroris, bahkan tanpa standar hukum yang jelas. Ketika konsep keamanan dipahami sempit oleh negara dan dilegitimasi dengan kekuatan militer, maka kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia menjadi taruhannya.
Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Ani mengatakan dampak paling fatal terhadap HAM dan demokrasi justru lahir dari pendekatan perang ( war model) ketika penanganan terorisme dilakukan militer. Draft Perpres ini justru masalah karena potensi kecenderungan menerapkan war model.
Prof. Ani juga menekankan bahwa terorisme harus dipahami secara komprehensif. Seseorang yang terlibat terorisme memang harus diproses sebagai pelaku kejahatan, tetapi pada saat yang sama ia juga sering merupakan korban dari proses indoktrinasi dan kekerasan ideologis. Karena itu, penanganan terorisme tidak cukup hanya dengan penindakan dan penghukuman, melainkan juga memerlukan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar siklus kekerasan tidak terus berulang.
Dalam konteks Indonesia, Prof. Ani mengingatkan bahwa pondasi kebijakan penanganan terorisme kita sejak awal adalah criminal justice system. Munculnya draft Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme menimbulkan pertanyaan serius: apakah kita sedang menggeser arah kebijakan ke pendekatan war model? Jika itu terjadi, maka seluruh warga negara akan terdampak, terutama karena adanya pasal-pasal yang bersifat karet dan multitafsir. Bukan hanya kebebasan sipil yang terancam, tetapi juga tatanan sosial dan demokrasi kita. Ia menambahkan bahwa TNI sebagai institusi pertahanan tidak seharusnya mengurusi urusan sipil, karena pelibatan tersebut berpotensi menggerus supremasi sipil dan prinsip negara hukum itu sendiri.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari dalam pandangannya bahwa Konstitusi kita sebenarnya sudah sangat jelas dalam mengatur kewenangan pertahanan dan keamanan. UUD NRI 1945 tidak membagi kewenangan itu, melainkan memisahkannya secara tegas. Ini adalah separation of function: militer tidak boleh masuk ke ruang sipil, dan aparat sipil seperti kepolisian juga tidak boleh bertindak seolah-olah menjalankan kekuatan militer. Pemisahan ini adalah fondasi negara hukum dan demokrasi.
Dalam kerangka itu, konstitusi juga menegaskan supremasi sipil atas militer, yaitu dengan tegas menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata adalah Presiden sebagai pemimpin sipil, bukan panglima dan bukan institusi militer itu sendiri. Masalahnya hari ini, Presiden kita memang sudah sipil secara status, tetapi masih merasa dan berpikir sebagai bagian dari militer. Ketika pemimpin sipil gagal memahami dominasi sipil, maka yang lahir adalah kerancuan sistemik dalam tata kelola negara.
Kegagalan memahami supremasi sipil itulah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyimpang, mulai dari revisi UU TNI yang membuka kembali ruang militer ke ranah sipil-politik, hingga munculnya rancangan Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Ini bukan sekadar soal teknis keamanan, tetapi penyimpangan terhadap pola pengaturan hukum yang telah digariskan oleh konstitusi.
Kesalahan paling mendasar adalah menggunakan logika pembagian fungsi, bukan pemisahan fungsi. Urusan pertahanan memang tugas TNI, dan keamanan adalah domain kepolisian. Tetapi ketika militer diberi kewenangan tambahan di wilayah sipil dengan dalih keamanan, yang terjadi adalah over-react negara. Dalam konteks rancangan Perpres ini, kita melihat dengan jelas perluasan kewenangan militer ke ranah sipil, yang ironisnya justru diperjuangkan oleh Presiden yang seharusnya menjadi representasi kepentingan sipil. Jika arah ini dibiarkan, maka supremasi sipil tinggal slogan, sementara praktiknya justru bergerak mundur. Draft perpres dalam penanganan terorisme ini berbahaya bagi kebebasan dan demokrasi di indonesia karena dapat membawa militer masuk ke wilayah penegkan hukum dan wilayah sipil yang tentu menjadi berbahaya bagi takyat.
Peneliti Senior Imparsial, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf Mengatakan adanya jurang yang serius antara kebutuhan nyata masyarakat dan respons pemerintah. Saat publik di Sumatera menunggu Perpres penetapan bencana nasional, yang justru muncul adalah rancangan Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Ini menunjukkan problem klasik: negara sibuk membangun agenda keamanan, sementara kebutuhan kemanusiaan masyarakat justru diabaikan.
Menurut Al Araf, terorisme adalah kejahatan pidana, sehingga penanganannya harus berada dalam koridor criminal justice system. Aktor utamanya adalah polisi, jaksa, dan pengadilan — bukan militer. Penegakan hukum wajib tunduk pada prinsip due process of law, mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga pengadilan. Pertanyaannya sederhana: apakah militer didesain dan dilatih untuk menjalankan due process of law? Jika TNI menangkap warga, lalu terjadi pelanggaran, mekanisme pengaduannya ke mana? Pra-peradilannya bagaimana? Ini akan menciptakan kekacauan hukum. Karena itu, pelibatan TNI melalui Perpres juga dinilai menabrak prinsip negara hukum dan semestinya diatur di level undang-undang, bukan Peraturan Presiden.
Masalah lain yang sangat berbahaya adalah definisi terorisme yang karet dan multitafsir. Al Araf mengingatkan bahwa bahkan Presiden pernah menyebut aksi demonstrasi sebagai makar atau terorisme. Kalau definisinya longgar dan perpres memberi ruang ‘operasi lainnya’ yang tidak jelas ukurannya, maka siapa pun bisa dituduh teroris. Dalam konteks ini, kelompok pro-demokrasi, pengkritik kebijakan pemerintah, hingga masyarakat sipil berisiko dibungkam melalui stigmatisasi terorisme.
Ia menarik paralel sejarah yang kuat: di era Orde Baru, kritik dibungkam dengan label komunis; hari ini, labelnya bisa berubah menjadi teroris. Menurut Al Araf, ini mencerminkan potensi politik ketakutan yang sedang dibangun negara. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa ketakutan yang terus dipelihara justru melahirkan perlawanan. Kasus di Aceh, ketika publik melawan tuduhan sabotase pembangunan dengan membongkar fakta lewat video, menunjukkan bahwa narasi keamanan yang dipaksakan tidak selalu dipercaya masyarakat.
Karena itu, Al Araf menilai rancangan Perpres ini tidak mendesak dan berisiko tinggi. Jika pemerintah tetap ingin melibatkan militer dalam konteks penanganan terorisme, maka langkah pertama yang wajib dilakukan adalah merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar prajurit yang melakukan pelanggaran dapat diadili di peradilan umum. Tanpa itu, pelibatan TNI hanya akan memperlemah supremasi sipil, merusak negara hukum, dan mengancam demokrasi.