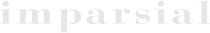Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan
Pemeriksaan Ahli dan Saksi Pemohon dalam Persidangan Uji Materiil Undang-undang TNI
Kembalikan Militer ke Fungsi Pertahanan dan Hentikan Praktik Impunitas di Peradilan Militer
Pada 14 Januari 2026, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan advokat dan pegiat hak asasi manusia menghadiri sidang uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Pemohon terdiri dari lima organisasi dan 3 perorangan Warga Negara Indonesia
Dalam kesempatan kali ini Pemohon menghadirkan dua Ahli, yaitu Prof. Muchamad Ali Safa’at (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya) dan Amira Paripurna, S.H., Ll.M., Ph.D (Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Selain itu Pemohon juga menghadirkan dua Saksi untuk membuktikan dalilnya, yakni Lenny Damanik (orang tua dari MHS (15 tahun) yang dibunuh oleh anggota TNI dan pelakunya hanya divonis 10 bulan penjara) dan Eva Pasaribu (anak dari jurnalis Rico Pasaribu yang mati karena dibakar rumahnya).
Dalam keterangannya, Ahli Prof. Muchamad Ali Safa’at menegaskan bahwa dalam negara demokrasi pasca-reformasi, peran TNI harus dibatasi secara tegas pada fungsi pertahanan negara sesuai Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 sebagai konsekuensi penghapusan dwifungsi ABRI dan penerapan supremasi sipil. TNI diposisikan sebagai alat negara yang profesional, netral dari politik, dan hanya dapat dikerahkan berdasarkan keputusan politik negara yang akuntabel dengan mekanisme checks and balances bersama DPR. Ahli menilai perubahan UU TNI berpotensi menyimpang dari agenda reformasi karena memperluas OMSP tanpa batasan yang jelas, mengurangi peran DPR, mempertahankan eksistensi peradilan militer yang secara nyata bertentangan dengan politik hukum UU TNI itu sendiri, serta membuka peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil, yang berisiko melemahkan demokrasi.
Sementara itu, Ahli Amira Paripurna, Ph.D. menegaskan bahwa peradilan sipil dan peradilan militer bertumpu pada logika yang berbeda: peradilan sipil berfungsi melindungi HAM dan membatasi kekuasaan negara melalui prinsip rule of law, sementara peradilan militer bersifat internal untuk menjaga disiplin dan hierarki. Dalam negara demokratis modern, yurisdiksi peradilan militer tidak layak diperluas untuk mengadili tindak pidana umum karena problem independensi dan risiko impunitas. Praktik komparatif, khususnya di Uni Eropa, menunjukkan tren pembatasan bahkan penghapusan peradilan militer pada masa damai. Terkait OMSP siber, keterlibatan TNI harus dibatasi ketat, bersifat last resort, sementara, berbasis keputusan politik negara, dan tunduk pada supremasi sipil.
Pemohon juga menghadirkan Saksi korban kekerasan militer yang secara nyata memperlihatkan dampak langsung dari masih berlakunya praktik impunitas di dalam tubuh peradilan militer. Saksi pertama, Eva Pasaribu, merupakan anak dari seorang jurnalis di Kabanjahe, Sumatera Utara, yang rumah keluarganya dibakar setelah sang ayah memberitakan praktik perjudian yang diduga melibatkan seorang anggota TNI. Peristiwa tersebut mengakibatkan kematian ayah, ibu, serta anak dari Saksi Eva Pasaribu. Sayangnya, dalang pembunuhan berencana itu hingga hari ini tidak pernah dihukum karena terkendala sistem peradilan militer yang tertutup
Saksi lainnya, Lenny Damanik, adalah ibu dari MHS, seorang anak yang meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan oleh seorang Babinsa di Sumatera Utara atas nama Sertu Riza Pahlivi. Dalam keterangannya, Saksi Lenny Damanik mengungkapkan proses hukum yang berjalan tidak memberikan keadilan bagi dirinya sebagai korban, Pelaku hanya dihukum penjara 10 bulan tanpa pemecatan dan tidak pernah ditahan selama proses persidangan. Saksi berlangsung baik dari segi transparansi, partisipasi keluarga, maupun berat ringannya pertanggungjawaban pidana pelaku.
Mirisnya keterangan yang disampaikan oleh kedua keluarga korban menunjukkan pola yang sama, yakni proses hukum yang tidak adil dan cenderung melindungi pelaku. Penanganan perkara melalui mekanisme peradilan militer berlangsung tertutup, minim pengawasan publik, dan menempatkan korban serta keluarganya pada posisi yang terpinggirkan. Dalam kedua kasus tersebut, keluarga korban tidak mendapatkan akses informasi yang memadai, tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses peradilan, serta menghadapi ketimpangan relasi kuasa ketika berhadapan dengan institusi militer.
Rangkaian keterangan ahli dan saksi di atas mengantarkan pada dua kesimpulan utama yang patut menjadi perhatian serius. Pertama, kecenderungan menguatnya militerisme tercermin dari meluasnya peran TNI di luar fungsi pertahanan, lemahnya kontrol sipil, serta tetap dipertahankannya yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum, yang secara nyata menyimpang dari agenda reformasi dan prinsip supremasi sipil. Kedua, praktik impunitas masih kerap terjadi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman para korban dan keluarga korban yang gagal memperoleh keadilan akibat proses peradilan militer yang tertutup, tidak transparan, dan menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional. Kedua kondisi ini menegaskan urgensi koreksi konstitusional untuk memastikan tegaknya negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, serta menghentikan segala bentuk militerisasi ruang sipil. Semoga yang mulia hakim konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon agar anggota militer yang terlibat tindak pidana umum dapat di adili dalam peradilan umum dan bukan peradilan militer.
Jakarta, 14 Januari 2026
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan
Narahubung
Riyadh Putuhena (Imparsial)
Andrie Yunus (KontraS)
Bhatara Ibnu Reza (De Jure)
Afif Abdul Qayim (YLBHI)