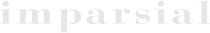Siaran Pers Imparsial
No. 033/Siaran-Pers/IMP/X/2025
Menyikapi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Bidang Pertahanan
“Rapor Merah untuk Menteri Pertahanan dan Pemerintah”
Pemerintahan Prabowo–Gibran akan segera memasuki tahun pertama kepemimpinannya pada 20 Oktober 2025. Selama satu tahun terakhir, terdapat sejumlah catatan penting di bidang pertahanan yang patut menjadi perhatian bersama.
Imparsial menilai bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran justru mempertegas rekonsolidasi militerisme di Indonesia. Alih-alih memperkuat agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir, pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif.
Kecenderungan ini mengancam prinsip dasar supremasi sipil, melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada bentuk pemerintahan yang semakin autokratis. Gejala ini terlihat jelas dari beberapa aspek berikut:
1. Militerisasi Ruang Sipil (Sekuritisasi)
Fenomena ini terjadi melalui tiga bentuk atau pendekatan:
Pertama, perluasan pelibatan TNI dalam ranah sipil atas nama operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu contoh menonjol adalah keterlibatan TNI dalam proyek strategis nasional (PSN) Food Estate di Merauke. Imparsial memandang program Food Estate, yang diikuti dengan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua—yakni Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentsuwri (Kabupaten Keerom), Yonif 802/Wimane Mambe Jaya (Kabupaten Sarmi), Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha (Kabupaten Boven Digoel), Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha (Kabupaten Merauke), dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap (Kabupaten Sorong)—tidak hanya menyimpang dari peran utama TNI, tetapi juga berpotensi memperburuk spiral kekerasan di Papua.
Konflik antara TNI dan masyarakat yang berujung pada pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, terlebih ketika Menteri Pertanian menyatakan bahwa pembukaan lahan seluas satu juta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih. Pengiriman pasukan tambahan secara ilegal di Merauke semakin memperlihatkan kecenderungan pendekatan keamanan (sekuritisasi) dan penguatan militerisme oleh pemerintah di Papua. Langkah ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai, dan justru memperkuat ketakutan masyarakat serta dominasi militer di wilayah rawan konflik tersebut.
Kedua, pelibatan TNI dalam tugas-tugas yang tidak termasuk dalam OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI. Keterlibatan militer dalam program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bergesernya peran TNI dari fungsi utama pertahanan ke ranah sipil. Padahal, tugas-tugas semacam itu seharusnya dijalankan oleh institusi sipil. Pelibatan ini tidak hanya mengganggu profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga melanggar ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 tentang TNI.
Ketiga, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Diantaranya adalah pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan pengangkatan Dirut Bulog sebanyak dua kali yang menempatkan militer aktif, yaitu Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang akhirnya memilih kembali berdinas di TNI usai beberapa bulan menjabat dan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog yang baru. Pengangkatan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 39 dan Pasal 47, yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Pengangkatan ini tidak hanya mencederai semangat reformasi TNI, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip supremasi hukum.
2. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan Kewenangan Berlebih
Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional atau DPN memang diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, namun kewenangan lembaga ini meluas secara berlebihan melalui Perpres No. 202 Tahun 2024. Pasal 3 huruf f peraturan tersebut menyebutkan bahwa DPN memiliki “fungsi lain yang diberikan oleh Presiden,” yang bersifat multitafsir dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Dengan klausul ini, DPN berpotensi menjadi lembaga superbody yang melampaui batas kewenangannya.
Imparsial menilai bahwa pembentukan DPN ini merupakan langkah yang berpotensi mengancam prinsip akuntabilitas dan kontrol demokratis di sektor pertahanan itu sendiri. Lebih jauh, komposisi keanggotaan DPN yang didominasi unsur militer dan elit eksekutif menunjukkan absennya prinsip check and balance yang semestinya dijaga dalam sistem pertahanan demokratis. Alih-alih memperkuat koordinasi kebijakan pertahanan nasional yang inklusif, pembentukan DPN justru menegaskan pola sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan lingkaran militer, yang bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan pasca-1998.
3. Penguatan Struktur Komando Teritorial (Koter) TNI
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menyampaikan dalam rapat dengan DPR bahwa pada tahun 2025 TNI akan membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di bawah Kodim untuk membantu percepatan pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Rencana ini jelas bertentangan dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI, yang menegaskan bahwa penggelaran kekuatan TNI harus dihindarkan dari bentuk organisasi yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis. Alih-alih melakukan restrukturisasi atau pengurangan jumlah Koter—sebagaimana diamanatkan dalam agenda reformasi TNI—pemerintah justru memperkuat struktur tersebut. Padahal, struktur Koter merupakan warisan Dwifungsi TNI di masa Orde Baru dan berpotensi kembali digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.
4. Kekerasan Militer dan Praktik Impunitas
Kasus kekerasan dan tindak pidana yang melibatkan anggota TNI terus berulang, namun penyelesaiannya tetap dilakukan melalui peradilan militer. Berdasarkan catatan Imparsial, sejak Januari hingga September 2025, prajurit TNI berulang kali terlibat dalam tindak pidana umum, seperti; penembakan bos rental mobil di Tangerang (Januari), Penyerangan Polres Tarakan (Februari), Penembakan warga sipil di Aceh dan Lampung, Pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru (Maret), serta penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI di Jakarta (Agustus).Kekerasan juga terjadi di internal militer, seperti kasus kematian Prada Lucky di Nusa Tenggara Timur akibat penganiayaan seniornya. Pola kekerasan yang berulang ini menunjukkan adanya masalah struktural dan kultural dalam tubuh TNI.
Sistem peradilan militer terbukti menciptakan ruang impunitas. Proses persidangan yang tertutup dan tidak memenuhi prinsip fair trial membuat keadilan sulit diwujudkan, terutama bagi korban sipil. Kasus-kasus seperti penembakan anak MAF di Serdang Bedagai (vonis 2 tahun 6 bulan), pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua (vonis 1 tahun), penyiksaan terhadap Jusni di Sulawesi (vonis 1 tahun 2 bulan), dan penyerangan warga Deli Serdang (vonis 9 bulan), semuanya berakhir dengan hukuman ringan dan jauh dari rasa keadilan. Lebih dari itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan militer juga sulit mendapatkan keadilan karena sistem peradilan yang tertutup dan abai terhadap prinsip keadilan gender.
Kondisi ini semakin diperparah dengan belum direvisinya UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, padahal TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU TNI telah menegaskan bahwa prajurit harus diadili di peradilan umum bila melakukan tindak pidana umum. Fakta bahwa ketentuan ini terus diabaikan memperkuat kesan bahwa anggota TNI kebal hukum. Reformasi peradilan militer merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Pemerintah dan parlemen wajib menindaklanjuti amanat ini sebagai bagian dari agenda reformasi TNI yang belum tuntas.
5. Legalisasi Militerisme Melalui Produk Hukum
Pengesahan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (revisi UU TNI) sangat bermasalah, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Proses revisi dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik, termasuk dari masyarakat sipil dan akademisi. Hingga pengesahan, tidak ada publikasi resmi mengenai naskah final yang disetujui DPR dan Pemerintah.
Selain revisi UU TNI, Penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa (Perpres 66/2025) semakin menguatkan gejala bangkitnya militerisme dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejak awal sudah menjadi kekhawatiran masyarakat sipil. Militerisme perlahan-lahan mulai disusun kembali di atas puing-puing reruntuhannya pasca Reformasi 1998. Bukan dengan sembunyi-sembunyi seperti penandatanganan MoU antara TNI dan lembaga sipil, melainkan secara kasat mata lewat pelibatan TNI dalam pengawalan Tugas dan Fungsi Jaksa yang diatur dalam Perpres tersebut.
Penerbitan Perpres 66/2025 Ini adalah model politik fait accompli yang sama sekali tidak sehat dan berdampak buruk bagi demokrasi. Seharusnya, yang dilakukan oleh Presiden adalah mencabut telegram tersebut dan bukan malah membentuk Perpres 66/2025. Dalam konteks ini Presiden Prabowo seolah-olah sedang membenarkan kesalahan Panglima yang terlanjur memerintahkan pengerahan pasukannya untuk mengamankan kejaksaan. Praktek kekuasaan yang tidak mengoreksi kesalahan penerapan hukum, tetapi justru melegalisasinya dengan menciptakan aturan baru membuktikan Indonesia semakin jauh dari cita negara hukum (rechstaat) dan sedang terjun bebas menuju negara berdasar kekuasaan (machstaat).
Selain itu, Presiden Prabowo juga berencana melibatkan TNI sebagai aparat penegak hukum dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d RUU tersebut, TNI diberikan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana siber. Rumusan ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa TNI bertugas mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara, bukan menjalankan fungsi penegakan hukum. Keterlibatan militer dalam proses penyidikan pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip civilian supremacy dan berpotensi mengancam kebebasan sipil serta demokrasi.
Imparsial menilai bahwa dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, negara justru mengalami kemunduran serius dalam agenda reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Pemerintah bukan hanya gagal melanjutkan reformasi TNI yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun, tetapi juga memperkuat militerisme dan mengembalikan peran militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan bahwa Kementerian Pertahanan gagal menunjukkan arah kebijakan yang jelas dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Anggaran yang stagnan, absennya dokumen strategis jangka panjang, dan minimnya transparansi publik menandai lemahnya tata kelola pertahanan selama periode ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan lebih banyak melakukan aktivitas politik yang mempertegas orientasi kekuasaan dibanding profesionalisme institusi. Dengan kondisi tersebut, kinerja Kementerian Pertahanan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran patut diberi rapor merah karena gagal memenuhi mandat reformasi sektor keamanan dan pertahanan. Jika pola kebijakan ini terus berlanjut, demokrasi Indonesia akan menghadapi ancaman serius berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelemahan supremasi hukum, dan munculnya model pemerintahan yang otokratis.
Berdasarkan uraian di atas, kami memberikan rapor merah sektor pertahanan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami menyimpulkan bahwa:
1. Presiden dan parlemen untuk mengevaluasi secara serius Menteri pertahanan karena beberapa kebijakannya yang cenderung tidak fokus membangun sektor pertahanan dan lebih fokus mengurusi masalah sosial politik . Beberapa kebijakan sektor pertahanan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan ham seperti mengembalikan dwi fungsi TNi melalui revisi UU TNI, pembentukan komando teritorial dan batalyon pangan, pembentukan dewan pertahanan nasional dengan kewenangan yang berlebihan dan multitafsir dan lainnya
2. Membangun konsolidasi masyarakat sipil yang kuat di dalam menghentikan segala bentuk kebijakan yang dapat membangkitkan militerisme dan berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia.
3. Kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang memberi ruang militerisasi wilayah siber, karena secara serius berbahaya bagi kebebasan sipil.
Jakarta, 19 Oktober 2025
IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor
Narahubung:
- 1. Wira Dika Orizha Piliang, Peneliti
2. Hussein Ahmad, Wakil Direktur
3. Annisa Yudha AS, Koordinator Peneliti
4. Riyadh Putuhena, Peneliti