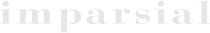Siaran Pers Imparsial
No. 042/Siaran-Pers/IMP/XII/2025
Dalam Rangka Memperingati Hari HAM Internasional 2025
“Hak Asasi Manusia Semakin Diabaikan”
Hari ini, 10 Desember 2025, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang ke-77. Meskipun Indonesia telah menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Konstitusinya, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan serius dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Ironisnya, negara yang seharusnya menjadi duty bearer, pihak yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, kerap justru menjadi aktor yang secara sengaja mengabaikan prinsip-prinsip tersebut.
Berikut beberapa catatan IMPARSIAL terkait kondisi tersebut dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2025:
Pertama, serangan terhadap Pembela HAM terus terjadi dan bahkan meningkat. Para pembela HAM dari berbagai latar belakang profesi, seperti jurnalis, pengacara publik, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, akademisi, aktivis keberagaman dan pembela HAM lainnya mengalami berbagai bentuk serangan seperti kekerasan fisik, ancaman teror, pelecehan dan kekerasan seksual, peretasan, kriminalisasi hingga pembunuhan, atas kerja-kerjanya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial baik dari pemberitaan media maupun laporan yang diterima secara lansung sepanjang tahun 2025, terdapat dua ratus dua puluh enam (226) peristiwa serangan terhadap pembela HAM. Di mana puncaknya terjadi pada bulan Agustus – September 2025, yaitu peristiwa kekerasan dan kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis di berbagai wilayah di Indonesia.
Kami menilai, permasalahan terkait perlindungan terhadap kerja-kerja pembela HAM ada pada tiga level, yakni di level jaminan hukum normatif, rendahnya komitmen negara, dan kesadaran masyarakat. Kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM, seringkali berupa kritik atau protes terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Hal ini menjadikan pembela HAM dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks ini, mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Sebaliknya, alih-alih memberikan perlindungan terhadap pembela HAM atau perempuan pembela HAM, Pemerintah cenderung melakukan pembiaran atas sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi kepada mereka.
Lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM, baik pada tataran hukum nasional maupun tingkat kesadaran, masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Pemerintah saat ini. Pemerintah seharusnya mengakui kerja-kerja pembela HAM dengan memberikan jaminan perlindungan hukum secara normatif, dan menghapus sejumlah instrumen hukum yang berpotensi menjerat pembela HAM, termasuk membatasi gerak dan kerja-kerja mereka. Lebih jauh, dalam konteks penanganan kasus serangan terhadap pembela HAM hingga kini Pemerintah justru masih melanggengkan praktik impunitas.
Misalnya, impunitas pada kasus pembunuhan Munir yang sudah bergulir selama lebih dari 20 tahun tanpa adanya kejelasan dalang pelakunya. Bukannya mendukung penuntasan kasus pelanggaran berat HAM pembunuhan Munir, Pemerintahan saat ini justru disinyalir menghambat penyelesaian kasus Munir dengan meminta Komnas HAM untuk menghentikan penyelidikan sementara. Selain itu, tekanan dan ancaman terhadap Komnas HAM juga diduga dilakukan oleh pejabat pemerintah guna menghentikan sejumlah kasus termasuk kasus Munir. Terbukti, hingga saat ini Komnas HAM belum menyelesaikan penyelidikan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia meski ketua Komnas HAM sudah menjanjikan hal tersebut kepada KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) beberapa waktu lalu.
Kedua, hak untuk hidup yang merupakan non-derogable rights (tidak dapat dikurangi dalam situasi/ kondisi apapun), terus dilanggar dengan terus menjatuhkan vonis pidana mati. Kendati Indonesia telah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sayangnya KUHP baru ini masih memuat pidana mati sebagai penghukuman meskipun keberlakuannya kini bersifat alternatif. Dalam KUHP baru ini diatur mekanisme “masa percobaan” selama 10 tahun yang wajib diberikan oleh hakim dalam memutus pidana mati. Jika dalam kurun waktu masa percobaan terpidana menunjukkan kelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
Namun Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah penting yakni menerbitkan aturan pelaksana terkait masa percobaan dan komutasi sehingga penerapan KUHP pada tahun 2026 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridor HAM. Peraturan pelaksana tersebut menjadi penting mengingat saat ini terdapat 723 terpidana mati yang hingga saat ini yang berada dalam deret tunggu eksekusi. Berdasarkan catatan Imparsial, 118 diantaranya telah menunggu lebih dari 10 tahun. Panjangnya deret tunggu ini menciptakan suatu fenomena yang dinamakan penghukuman dua kali (double punishment) yang mana sebetulnya merupakan pelanggaran lain terhadap hak asasi manusia.
Hukuman mati merupakan hukuman yang sangat keji serta sejatinya bertentangan dengan Konstitusi dan instrumen HAM lainnya. Selain itu, hukuman mati tidak layak diterapkan di Indonesia karena sistem penegakan hukum kita masih sangat rentan terhadap korupsi dan praktik unfair trial seperti penyiksaan dan salah tangkap. Praktik unfair trial ini rentan terjadi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan di pengadilan yang mengabaikan hak-hak tersangka/ terdakwa. Imparsial mendesak Pemerintah saat ini untuk melakukan moratorium resmi terhadap eksekusi mati mengingat berbagai persoalan terkait penerapan hukuman mati sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Imparsial juga mendesak untuk jangka panjang Pemerintah Indonesia menghapuskan hukuman mati secara keseluruhan dalam sistem pidana Indonesia dan mengutamakan reformasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan.
Ketiga, Agenda Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Hanya Retorika. Sepanjang tahun 2025, Imparsial menemukan setidaknya 27 kasus pelanggaranpelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. Temuan-temuan pelanggaran KBB yang menonjol adalah diantaranya; penolakan pendirian rumah ibadah; pelarangan pelaksanaan ibadah baik secara individu maupun berkelompok, dan penerbitan regulasi atau kebijakan yang bersifat diskriminatif oleh sejumlah pemerintah daerah. Kasus-kasus pelanggaran tersebut terjadi antara lain di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, hingga di Papua.
Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebelas kasus, yang menunjukkan bahwa provinsi ini masih menjadi episentrum persoalan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan. Sementara itu, tiga kasus masing-masing terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, serta Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, hingga Papua masing-masing satu kasus. Dengan luasnya persebaran pelanggaran hak atas KBB tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak atas KBB masih menjadi persoalan nasional hingga kini. Pelaku pelanggaran terdiri dari aktor negara dan aktor non-negara mulai tokoh agama, warga, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, Korban pada umumnya adalah anggota kelompok minoritas agama atau keyakinan di daerah tersebut.
Dari semua peristiwa yang ada, jenis pelanggaran terhadap hak untuk melaksanakan ibadah menjadi yang paling dominan dilanggar, disusul pelanggaran terhadap hak untuk mendirikan rumah ibadah dan hak untuk menyiarkan ajaran agama atau ekspresi keagamaan. Imparsial memandang, dominasi Jawa Barat dalam catatan pelanggaran KBB bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini berulang kali menempati posisi teratas dalam laporan tahunan Imparsial dan berbagai organisasi HAM. Faktor penyebabnya antara lain adalah kuatnya regulasi daerah yang diskriminatif, tingginya pengaruh kelompok intoleran dalam memengaruhi kebijakan lokal, lemahnya keberpihakan aparat terhadap kelompok rentan, serta rendahnya komitmen negara dalam menyediakan akses pemulihan bagi korban.
Keempat, Reformasi TNI Mengalami kemunduran serius. Dalam konteks reformasi TNI memang sejumlah capaian positif reformasi sektor keamanan seperti pemisahan TNI dan Polri, dan penghapusan doktrin Dwifungsi berhasil dilakukan pada awal Reformasi. Namun, 27 Tahun berlalu sejak Reformasi 1998, agenda reformasi TNI semakin ditinggalkan dan bahkan justru mundur ke belakang. Bahkan, dalam konteks penghapusan Dwifungsi dan pemisahan TNI dan Polri yang merupakan capaian positif saja, kini justru semakin mengkhawatirkan dikarenakan pada praktiknya peran-peran TNI di ranah sipil (sosial-politik) semakin intrusif.
Hal ini semakin dipertegas dengan pengesahan revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 melalui UU No. 3 Tahun 2025 yang dinilai sebagai bentuk kemunduran serius dalam agenda reformasi TNI. Imparsial menegaskan bahwa revisi tersebut membuka kembali ruang perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan, melemahkan prinsip supremasi sipil, serta mengaburkan batas antara ranah militer dan keamanan dalam negeri. Revisi ini juga menghidupkan kembali pola Dwifungsi militer secara de facto melalui penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dan perluasan operasi militer selain perang tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Dengan demikian, aturan baru ini bukan hanya bertentangan dengan amanat reformasi 1998, tetapi juga berpotensi menciptakan overreach militer yang mengancam konsolidasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Sejumlah agenda reformasi TNI yang tersisa, seperti restrukturisasi komando teritorial, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan reformasi peradilan militer, sudah seharusnya menjadi prioritas. Dalam konteks reformasi peradilan militer, Imparsial secara konsisten menilai bahwa sistem peradilan militer saat ini minim akuntabilitas, tidak transparan, dan kerap gagal memenuhi prinsip dan standar fair trial. Imparsial menilai bahwa sistem penegakan hukum di lingkungan peradilan militer masih tertutup, tidak independen, dan sejatinya bertentangan dengan prinsip equality before the law, karena membuka ruang bagi impunitas terhadap anggota TNI yang diduga melakukan kejahatan. Oleh karena itu, reformasi peradilan militer, termasuk memindahkan yurisdiksi prajurit yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di peradilan umum, menjadi keharusan untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum serta menjamin bahwa anggota TNI dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan transparan. Reformasi peradilan militer semakin penting dilakukan mengingat dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang terdapat sejumlah kasus impunitas yang terungkap di antaranya kasus pembunuhan anak MHS dan MAF di Sumatera Utara yang hanya divonis masing-masing 9 bulan dan 2,5 tahun penjara. Kasus lain yang menjadi perhatian publik adalah kasus pembunuhan bos rental mobil di Tangerang yang kasusnya dikorting dari sebelumnya divonis seumur hidup menjadi 15 tahun penjara pada tingkat Mahkamah Agung. Kasus-kasus Impunitas tersebut belum termasuk kasus-kasus lain yang tidak terpantau publik di Peradilan Militer.
Kelima, Agenda Reformasi Kepolisian Macet Total. Kendati saat ini Pemerintah telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, namun sejumlah catatan negatif dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian masih kerap terjadi. Salah satunya adalah terkait kultur kekerasan di tubuh Kepolisian. Kepolisian masih jauh dari cita-cita pemolisian yang demokratis di mana kepolisian menjunjung tinggi HAM dan tata negara hukum. Sepanjang tahun 2025 ini kemarahan publik memuncak akibat dari kasus dilindasnya Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 pada saat demonstrasi menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR. Kasus kekerasan Polisi dalam penanganan demonstrasi terjadi di berbagai daerah, seperti di Surabaya dan Bandung, termasuk kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Pasundan (UNPAS), di mana polisi menembakkan gas air mata kepada mahasiswa hingga ke dalam area kampus dan pos medis. Peristiwa itu mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami luka, sesak nafas, hingga pingsan. Kultur kekerasan ini harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Pada titik ini, dalam jangka pendek Kapolri harus mengevaluasi pola peenanganan aksi massa atau demonstrasi agar menghormati prinsip hak asasi manusia dan menggunakan kekuatannya secara terukur dan legitimate.
Selain itu, mengingat masih adanya penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, Kapolri juga harus melakukan evaluasi terhadap seluruh izin penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Evaluasi dapat berupa tes mental dan psikologi ulang yang dilakukan secara berkala kepada seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali. Hasil tes mental dan psikologi yang dilakukan tersebut harus dijadikan dasar apakah anggota kepolisian tersebut diperkenankan menggunakan senjata api atau tidak.
Dalam jangka menengah Kapolri perlu merealisasi ide penggunaan body cam yang dilekatkan pada anggota Polri ketika bertugas. Penggunaan body cam penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemolisian yang diperlukan sebagai deterrence guna mencegah pelanggaran termasuk penggunaan kekuatan berlebihan. Selain itu, dalam jangka panjang untuk mencegah terulangnya fatalitas akibat penggunaan senjata api, Kapolri perlu memikirkan pengurangan penggunaan senjata api dan menggantikannya dengan senjata kejut listrik (taser) yang lebih tidak mematikan sebagaimana sudah digunakan di banyak negara.
Lebih dari itu, Kapolri juga perlu melakukan pembaharuan terhadap metode pelatihan anggota kepolisian yang lebih vokasional. Selama ini pelatihan anggota kepolisian terutama Bintara dan Tamtama mengedepankan olah fisik yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sudah seharusnya pendidikan anggota kepolisian menekankan pada keahlian vokasional yang sesuai pada hak asasi manusia dan demokrasi. Polri perlu menyadari, bahwa munculnya desakan reformasi kepolisian termasuk menempatkan Polri di bawah kementerian adalah akibat reformasi kepolisian yang selama ini terhenti dan enggan dilanjutkan.
Keenam, Kekerasan Bersenjata di Papua meningkat dan Resolusi Konflik Papua Berhenti. Kebijakan sekuritisasi di Papua masih terus berlanjut dengan pengiriman pasukan non organik hingga penebalan jumlah militer organik dan personel Brimob Polri di tanah Papua. Sementara itu upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua tak kunjung dituntaskan. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Project Multatuli, hingga tahun 2025 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 56. 517 prajurit TNI, baik organisk maupun non-organik, dan mengirimkan 26.660 personel Polri ke tanah Papua. Akibatnya korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi antara kelompok bersenjata di Papua dengan aparat TNI/Polri.
Selain itu, potensi konflik di Papua semakin mengkhawatirkan akibat pemekaran wilayah dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti program Food Estate di Merauke. Imparsial memandang program Food Estate yang diikuti dengan penambahan dan pembentukan lima batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di tanah Papua tidak hanya penyimpangan peran TNI tetapi juga berpotensi memperparah spiral kekerasan. Konflik antara TNI dengan masyarakat yang menimbulkan pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pembukaan lahan satu juta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih.
Kebijakan sekuritisasi Papua yang terus berlanjut menjadi bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Alih-alih menepati janji untuk mengutamakan dialog dan pendekatan damai, langkah ini justru memperburuk situasi, menambah ketakutan masyarakat dan memperkuat pengaruh militer di wilayah yang sudah rentan konflik. Jika pemerintah Indonesia tidak belajar dari kesalahan masa lalu seperti kasus kekerasan militer dan pelanggaran HAM di Aceh dan Timor Leste maka tuntutan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia menjadi semakin kuat.
Jakarta, 10 Desember 2025